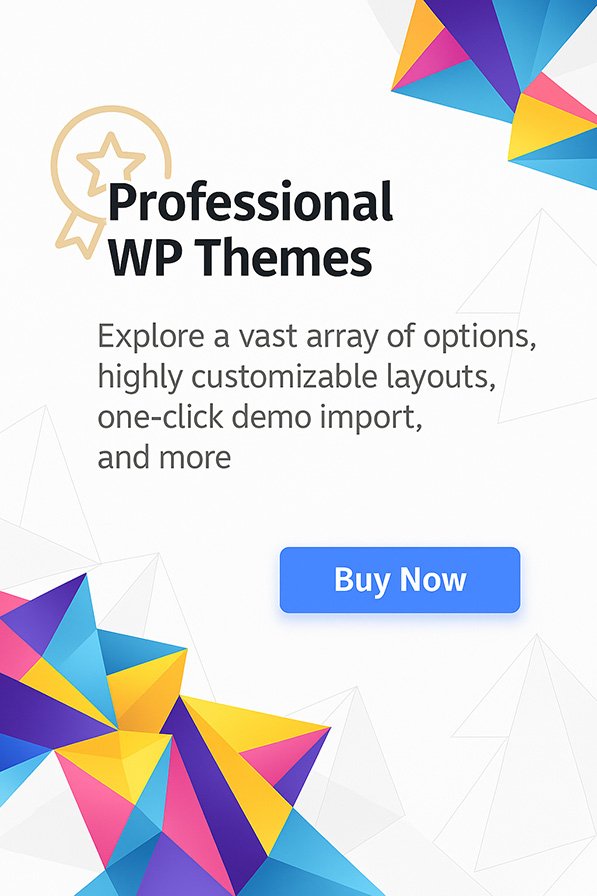Sebuah Bisikan di Bawah Terik Mentari dan di Riuh Pasar Kehidupan
By Benyamin Marotno, S.Pd.
Pelajaran yang Tak Terdengar dari Mikrofon
Pagi itu, di bawah langit yang biru, kami berdiri di lapangan yang sama. Panas mentari terasa menyengat, cahayanya begitu kuat hingga membuat sedikit menyipitkan mata. Di depan sana, suara pembina upacara terdengar tegas melalui pengeras suara, menggema di seluruh penjuru. Sebuah pesan penting tentang disiplin, tentang karakter, tentang pentingnya membangun akhlak mulia untuk masa depan.
Itu adalah pelajaran yang resmi. Pelajaran yang dirancang untuk didengar.
Namun, di tengah khidmatnya suasana, coba kita alihkan sejenak fokus kita, Sahabat. Mungkin perhatian jatuh pada sosok seorang guru yang berdiri di barisan belakang. Ia tidak memegang mikrofon. Ia hanya menatap murid-muridnya dengan sorot mata yang teduh, sesekali tersenyum tipis saat melihat barisan yang lurus. Atau menegur lembut jika ada yang mengobrol dan meribut di barisan belakang. Di dalam tatapannya, ada pancaran harapan, kebanggaan, dan doa yang tak terucap.
Atau mungkin kita melihat seorang kakak kelas yang diam-diam merapikan letak topi adik kelasnya yang miring, tanpa perlu berkata-kata. Sebuah sentuhan kecil, sebuah kepedulian sunyi yang tidak akan pernah diumumkan sebagai prestasi.
Saat itulah kita sadar. Pelajaran yang paling meresap ke dalam jiwa seringkali bukanlah yang datang dari pengeras suara.
Pelajaran terdalam justru datang dari momen-momen sunyi yang tak terduga. Guru di barisan belakang itu, dengan tatapannya, dengan teguran lembutnya, baru saja mengajarkan kita tentang ketulusan. Kakak kelas itu, dengan sentuhan tangannya, baru saja mengajarkan kita tentang kepedulian.
Mereka adalah “guru tak terduga” di tengah upacara yang khidmat. Momen itu menyadarkan kita, ruang kelas kehidupan ini tak pernah libur. Ia hadir bahkan di tengah lapangan upacara yang terik.
Cermin di Riuh Pasar Kehidupan
Pelajaran itu tidak berhenti saat barisan dibubarkan. Mari kita bergeser sejenak, Sahabat, dari lapangan yang teratur ke sebuah panggung lain yang lebih riuh dan nyata: mungkin di hiruk pikuk Pasar di jam sibuk. Di sini, tidak ada amanat pembina, yang ada hanya riuh suara pedagang, tawar-menawar yang sengit, dan aroma keringat yang berbaur dengan wangi rempah, atau sayur busuk yang belum sempat diangkat petugas kebersihan.
Di tengah keramaian itu, mata kita mungkin tertuju pada seorang (ibu) paruh baya di lapak sayurannya. Seorang pembeli, mungkin seorang ibu muda yang terburu-buru, membayar dan lekas pergi. Beberapa saat kemudian, sang Ibu pedagang menghitung uangnya dan raut wajahnya berubah. Ia bergegas dari balik lapaknya, sedikit berlari sambil memanggil ibu muda tadi, “Nak, uangnya kelebihan tadi, ini kembaliannya!”
Tidak ada yang memberinya penghargaan. Tidak ada kamera yang merekam. Transaksi itu mungkin hanya bernilai puluhan ribu.
Namun, di tengah desakan ekonomi dan riuhnya pasar, ia baru saja memberikan kuliah paling mahal tentang integritas.
Di sinilah filsafat Stoikisme kuno bertemu dengan kearifan lokal. Para filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada hal-hal eksternal (seperti uang atau pujian), melainkan pada kebajikan internal yang bisa kita kendalikan sepenuhnya: kejujuran, keadilan, dan keberanian kita. Ibu di pasar itu adalah seorang Stoik sejati. Ia memilih ketenangan jiwa yang datang dari kejujuran (amanah) daripada keuntungan sesaat. Ia adalah seorang profesor di universitas kehidupan, yang mengajarkan bahwa karakter adalah mata uang tertinggi.
Dari guru yang tulus di lapangan upacara hingga pedagang yang jujur di riuh pasar, kita melihat sebuah kebenaran universal: setiap jiwa, dalam setiap profesi, adalah cermin. Setiap tindakan kita memantulkan nilai yang kita anut, menjadi pelajaran bagi siapa pun yang melihatnya.
Sebenarnya kita semua Menjadi Murid yang Tak Pernah Lulus
Lalu, apa muara dari semua kesadaran ini? Jika setiap kita adalah guru dan cermin bagi yang lain, apakah ini menjadi beban yang berat?
Justru sebaliknya. Kesadaran ini bukanlah sebuah beban untuk menjadi “guru yang sempurna”, melainkan sebuah undangan penuh kasih untuk menjadi “murid yang tak pernah lulus.”
Satu-satunya hal yang aku tahu adalah bahwa aku tidak tahu apa-apa.” Inilah titik awal dari segala kearifan. Kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita selalu punya ruang untuk belajar, untuk tumbuh, untuk memperbaiki diri.
Saat kita menerima peran sebagai murid abadi, kita tidak lagi terbebani untuk “terlihat baik”, melainkan fokus untuk “menjadi baik”. Perbaikan diri bukan lagi kewajiban tahunan, tapi menjadi napas harian. Kita belajar sabar dari kemacetan lalu lintas, belajar ikhlas dari rencana yang gagal, belajar syukur dari secangkir teh di pagi hari.
Perintah untuk terus menambah ilmu ini adalah mandat untuk menjadi murid seumur hidup. Karena hanya dengan terus mengisi gelas diri kita, kita bisa memancarkan cahaya bagi sekitar. Bukan karena kita ingin mengajar, tapi karena sebuah lilin yang menyala, secara alami akan menerangi sekelilingnya.
Jadi, Sahabat,,,,,,, tidak peduli apa profesi kita, di panggung mana kita berdiri hari ini—apakah di depan kelas, di balik meja kasir, di ruang rapat, atau di dapur rumah kita. Kita semua adalah bagian dari rantai pengajaran agung ini.
Mari kita jalani peran ini dengan kesadaran penuh. Bukan dengan kesombongan seorang guru, tapi dengan kerendahan hati seorang murid yang tak pernah berhenti belajar.
Mari Kita refleksi sahabat.
Berbagi adalah Indah.